Peringatan 20 tahun tsunami Aceh: Cerita dua penyintas yang memilih tinggal di zona berbahaya – 'Kita sudah enggak takut lagi tinggal di pantai'

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Dwiki Marta
- Penulis, Heyder Affan
- Peranan, Wartawan BBC News Indonesia
- Waktu membaca: 16 menit
Menjelang peringatan 20 tahun tsunami Aceh, para penyintas dan masyarakat terdampak mengenang keluarga dan kerabatnya yang menjadi korban. Namun di sisi lain mereka dituntut untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana serupa di masa depan.
Suara pecahan ombak di bibir pantai Ulee Lheue, Banda Aceh, terdengar lirih saat kami bertemu dua perempuan penyintas tsunami Aceh 2004.
Terdengar pula samar-samar deru mesin perahu nelayan yang sesekali melintas saat air surut.
Namun tangisan sesenggukan Safiatuddin alias Mak Dek (56 tahun) dan Agustina Dewi (47 tahun) justru yang lebih sering kami dengar di pagi itu.
"Saya teringat terus, saya tidak bisa melupakannya," kata Mak Dek kepada saya dan videografer Dwiki Marta, Rabu, 13 November 2024 lalu.
Suaranya terdengar parau.
Kami bertemu keduanya di warung kopi dan mie milik Mak Dek. Mereka tengah mengobrol. Ada dua atau tiga perempuan lainnya kemudian bergabung.
Mak Dek dan Dewi adalah warga gampong (setingkat desa) Ulee Lheue. Letaknya persis di tepi laut.
Desa ini merupakan salah-satu yang rusak parah akibat tsunami 26 Desember 2004. Jumlah penduduknya jauh berkurang setelah bencana itu.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Heyder Affan
Di Kota Banda Aceh dan kota-kota pesisir barat, lebih dari 160.000 orang—hampir 5% dari jumlah penduduk keseluruhan—tewas dihempas tsunami setinggi hingga 35 meter.
Tsunami raksasa itu dipicu gempa bumi berkekuatan magnitudo 9,3. Ini adalah tsunami paling mematikan dalam catatan sejarah.
Baca juga:
Kini, 20 tahun kemudian, pikiran Mak Dek tidak sepenuhnya dapat beranjak dari bencana dahsyat itu.
Dia kehilangan ibu, suami dan dua anaknya yang masih kecil. Jasadnya tidak pernah ditemukan.

Sumber gambar, Getty Images/Roni Bintang
Ibunya terseret arus saat Mak Dek berusaha menyelamatkannya di dalam sebuah masjid.
"Saya selalu teringat mamak. Kalau mau ke masjid, rasanya saya tidak bisa," Mak Dek terisak.
Masjid yang dimaksud Mak Dek adalah Masjid Baiturrahim. Lokasinya tak jauh dari lokasi kami bertemu.
Saat gelombang tsunami menerjang pada hari Minggu pagi itu, sebagian warga—termasuk Mak Dek—menyelamatkan diri masuk ke dalam masjid itu.
Walaupun rusak di sana-sini akibat terjangan gelombang air laut, bangunan masjid itu masih berdiri kokoh.
Baca juga:
Di belakang masjid itulah, Mak Dek—panggilan akrab Safiatuddin—dulu tinggal bersama suami, dua anak, serta ibunya.
Keluarga Mak Dek dan orang-orang yang tinggal di Ulee Lheue memang amat akrab dengan masjid itu.
Sebagian warga beribadah atau bertemu untuk sebuah acara di sana. Dan ketika bencana itu datang, mereka berharap pula kepadanya.
'Air naik, air naik...'
"Air naik, air naik…!"
Seiring kehadiran gelombang itu, Mak Dek—berbadan gempal—berusaha menggendong ibunya yang tengah sakit.
Suami dan dua anaknya tidak ada di rumah.
"Mereka mau lihat rumah yang runtuh karena gempa," ujarnya.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Dwiki Marta
Di dalam masjid, dalam kondisi panik, dia bersama ibu dan sebagian tetangganya memilih sudut yang dianggapnya aman.
"Kami diblender, diputar [oleh gelombang air] di situ," ungkap Mak Dek.
Kelak terungkap ada tujuh orang yang selamat di bangunan itu. Mereka berhasil naik ke lantai atas.
Namun tidak bagi ibu kandung Mak Dek.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Dwiki Marta
"Mamak terlepas dari tangan..." Mak Dek tak bisa membendung tangisannya.
Dia terpisah dari ibunya, tangannya tak kuat memegang erat-erat badannya.
Ombak ganas membuatnya dan orang-orang lain di dalam masjid terbawa arus.
Dia tak pernah menemukan jasad ibunya, suaminya, dan dua anaknya sampai sekarang.

Sumber gambar, Wikipedia/Tropenmuseum

Sumber gambar, Wikipedia/usgs

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Heyder Affan
"Anak pertama [usianya] mau sembilan tahun. Dia pandai, cepat masuk sekolah. Namanya Saputra Ramadana, panggilannya Putra."
"Yang satu lagi, Ikram Muhammad, kalau enggak salah usianya tiga tahun."
Suara Mak Dek terdengar tercekat, lalu air matanya meleleh, lalu sesenggukan.
Wawancara beberapa kali kami hentikan.
Sambil kembali meminta maaf, saya lebih dari sekali berkata perlahan: Jika Mak Dek merasa tidak nyaman, wawancara dapat diakhiri.
Baca juga:
Duduk di sebelah Mak Dek, Agustina Dewi—yang juga kehilangan ibunya saat tsunami 2004—justru yang menjawabnya.
"Dengan curhat dengan bapak ini, lega. Rasanya air mata yang tumpah ini bikin lega, ya kan kak."
Dewi memanggil tetangganya itu dengan sebutan "kak".
Mak Dek dan Dewi memang sampai sekarang tidak bisa melupakan apa yang mereka alami 20 tahun silam.
'Setiap ada hujan lebat, saya takut dan lari'
Seiring berlalunya waktu serta dilatari faktor lain, Dewi mengaku ingatan traumatis atas kejadian itu tidak seekstrem 15 tahun silam.
Dia lalu teringat, selama lima tahun setelah tsunami, setiap hujan turun atau langit berubah gelap, dia lari sekuat tenaga ke lokasi yang dianggapnya aman.
Ketika itu Dewi, suami dan anaknya masih tinggal di barak pengungsian.
"Lima tahun saya menahan trauma," kata Dewi sesenggukan.

Sumber gambar, Jewel Samad/Chaideer Mahyuddin/AFP
Sarjana pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh ini menyesal saat itu tak menghubungi psikolog.
Dia mengaku belum tahu apa-apa terkait trauma yang dialaminya.
"Bodohnya saya waktu itu, padahal banyak psikolog waktu itu [yang datang ke Aceh]," Dewi mengaku.
Baca juga:
Ketika gempa dan tsunami menerjang Aceh, Dewi baru setahun menikah dan sudah memiliki anak berusia sembilan bulan. Namanya Rizki Risnaldi Saputra.
Rumah Dewi tak begitu jauh dari rumah Mak Dek—tidak jauh dari bibir pantai.
Tetapi saat gelombang ombak raksasa menerjang pesisir Banda Aceh, Dewi sedang tidak tinggal di Ulee Lheue.
Dia dan anaknya berada di rumah keluarganya di perumahan Cade, Banda Aceh—tak jauh juga dari laut. Ada acara keluarga di sana yang juga dihadiri ibunya.

Sumber gambar, Bay Ismoyo/Chaideer Mahyuddin/AFP

Sumber gambar, Bay Ismoyo/Chaideer Mahyuddin/AFP
Setelah gempa, Dewi dan keluarganya tak mengetahui bahwa tsunami sudah mengintai.
Lalu, "saat air datang, semua jadi gelap. Kami terpencar [terbawa arus air]."
Dewi yang mahir berenang berusaha menyelamatkan anaknya yang terus merengek.
Dia sempat berusaha menyelamatkan dan memasukkan anaknya ke kulkas yang mengambang di dekatnya, tapi dia batalkan.
Seraya menggendong anaknya ("dia menjambak rambut saya erat-erat," katanya), tangan Dewi berhasil menggapai pohon kelapa yang tumbang.

Sumber gambar, Kazuhiro Nogi/Chaideer Mahyuddin/AFP
Anaknya sempat terlepas, tetapi dia bisa menggapainya kembali ("Alhamdulillah, dia masih bernapas," dia mengingat).
Sebagian besar saudara-saudaranya selamat, tetapi ibunya hilang terbawa gelombang.
"Kalau ingat tsunami, ingat lagi mamak."
Dewi tak kuasa menahan tangisnya.
Baca juga:
Arus air akhirnya menghanyutkan Dewi dan anaknya yang berusia sembilan bulan ke daerah di dekat kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kecamatan Darussalam, Banda Aceh.
Sekelompok mahasiswa menyelamatkannya. Sebulan kemudian dia baru bertemu suaminya.
Adapun Mak Dek, yang terhanyut dan terkatung-katung di laut selama empat hari, berhasil diselamatkan nelayan.

Sumber gambar, Getty Images/Roni Bintang
Dia kemudian bertemu salah-seorang kakaknya yang selamat di lokasi pengungsian.
Dulu Mak Dek selama berbulan-bulan masih berharap untuk dapat menemukan jasad ibu, suami dan dua anaknya.
Dia menyudahi upaya pencarian tiga orang kesayangannya itu setelah seseorang berujar kepadanya "tidak usah dicari lagi, doakan saja ibu, suami dan anak-anakmu."

Sumber gambar, Getty Images/Roni Bintang
Mengapa Mak Dek dan Dewi kembali tinggal di Ulee Lheue yang rawan tsunami?
Seperti warga Banda Aceh yang terdampak tsunami, Mak Dek dan Dewi sempat tinggal di lokasi pengungsian yang disediakan pemerintah.
Mereka juga kadang menumpang di rumah orang lain. Namun mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal kembali di Ulee Lheue.

Sumber gambar, Getty Images/Roni Bintang
Ketika dihadapkan keputusan apakah kembali tinggal di Ulee Lheue atau tidak, Dewi sempat bimbang.
Dia semula ingin kembali ke Meulaboh—kota di pesisir pantai barat Aceh yang juga luluh lantak akibat tsunami, tempat tinggal keluarga besarnya.
Tetapi suami dan anaknya keberatan. Suami Dewi adalah warga asli Ulee Lheue.
Saat otoritas pemerintah menganjurkan agar warga yang tinggal di pesisir yang masuk kategori berbahaya (sudah pasti Desa Ulee Lheue masuk di dalamnya) untuk pindah ke lokasi yang lebih aman, Dewi dan Mak Dek menolaknya.

Sumber gambar, Getty Images/Roni Bintang
Mereka bahkan kembali ke desanya lebih awal dengan memasang tenda ala kadarnya di dekat reruntuhan rumahnya.
Walaupun semula merasa belum siap kembali ke lokasi bekas rumahnya yang hancur akibat tsunami di Ulee Lheu, Dewi akhirnya tak menolak ajakan suami dan anaknya.
Keluarga suaminya memiliki ikatan sosial dan ekonomi di kampung itu.
"Saya harus siap mental [tinggal di Ulee Lheue]," akunya.
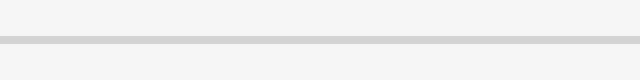
BBC News Indonesiahadir di WhatsApp.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.
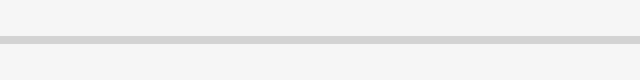
Alasan lainnya? "Saya punya prinsip begini: kemana pun saya pergi, saya mati, akan mati juga."
Ini juga diamini Mak Dek. Kendati mengaku masih trauma setiap salat di masjid Baiturrahim, Mak Dek tak punya alasan kuat untuk meninggalkan kampungnya.
"Ini tanah kelahiran, dibesarkan di sini. Orang tua meninggal di sini. Orang tua suami saya juga meninggal di sini. Ada makamnya di sini," ujarnya.
Lagi pula, "di tempat lain, mana bisa kita cari rezeki."

Sumber gambar, Chaideer Mahyuddin/AFP
Atas bantuan kakaknya, Mak Dek diberi kepercayaan mengelola warung kopi dan mie sejak enam tahun lalu.
"Daripada keluyuran ke sana-sini," kata Mak Dek menirukan alasan kakaknya.
Bangunan setengah permanen miliknya itu terletak kurang dari dua meter dari bibir pantai.
Suara ombak terdengar lirih dari warung Mak Dek. Di warung itulah kami bertemu dirinya dan Agustina Dewi.
Alasan di balik pilihan kembali ke kampungnya, seperti diutarakan Mak Dek dan Dewi, sering saya dengar dari para penyintas tsunami 2004 di Aceh.
Selain alasan ekonomi, mereka memiliki keterikatan sosial-budaya dengan gampong asalnya.
Inilah alasan terkuat kenapa Mak Dek dan Dewi memilih kembali ke gampong atau desa asalnya.

Sumber gambar, Chaideer Mahyuddin/AFP
Dan masalah ini bukannya tidak disadari sejak awal oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) untuk Aceh dan Nias.
BRR adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia.
Mereka bertugas mengawasi dan mengkoordinasi upaya-upaya bantuan di wilayah yang rusak akibat gempa dan tsunami.
Pada awal-awal, lembaga ini pernah merancang cetak biru (blue print) penataan tata ruang Aceh pascatsunami. Namun faktanya, rancangan itu tak pernah bisa direalisasikan.

Sumber gambar, Chaideer Mahyuddin/AFP
BRR tidak mampu membendung keputusan masyarakat di Aceh untuk kembali ke rumah asalnya.
Dan suatu saat, Kepala BRR (almarhum) Kuntoro Mangkubroto pernah berujar "blue print bukan harga mati".
Secara implisit, dalam wawancara dengan BBC News Indonesia sekian tahun lalu, Kuntoro mengatakan, bahwa pihaknya sudah menggariskan bahwa sudah ada imbauan agar warga tidak lagi menempati lokasi bekas rumahnya di zona berbahaya.
"Ada pemikiran itu, tapi enggak jalan," katanya.
Baca juga:
Dan itulah yang terlihat saat kami berada di Banda Aceh pertengahan November 2024 lalu.
Memang di kawasan tertentu sudah tidak ada pemukiman, tapi di wilayah lainnya, seperti di kampung tempat Mak Dek dan Dewi tinggal, sudah berdiri rumah-rumah yang saling berimpitan.
Masalah ini kemudian kami tanyakan kepada penjabat sementara Gubernur Aceh Safrizal ZA.

Sumber gambar, Getty Images
Dia mengakui saat BRR melakukan rekonstruksi pascatsunami, sudah ada penolakan dari warga.
Arus penolakan sulit dihentikan. Safrizal, dan barangkali otoritas terkait di mana pun di Indonesia, tak mampu membendungnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pernah menyebutkan bahwa sekitar lima juta penduduk Indonesia tinggal di daerah yang rawan tsunami.
Upaya relokasi sulit dilakukan, walaupun jelas-jelas mereka tinggal di zona berbahaya.
Ini bukanlah khas Aceh, karena masalah yang sama juga terjadi di wilayah lain di Indonesia.

Sumber gambar, Getty Images/Ulet Ifansasti
Namun tidak berarti pemerintah berpangku tangan, setidaknya itu yang terekam dari ucapan Safrizal.
Dia berujar, jika masyarakat tetap memilih bertahan di pesisir, maka mereka harus mengetahui secara persis apa yang harus dilakukan bila tsunami datang.
"Kalau bencana tak bisa kita pindahkan, kita pindah juga enggak mau, maka yang ada adalah living harmony with disaster (hidup berdampingan dengan bencana).
"Artinya tetap tinggal di tepi laut, tetapi tahu bahaya dan tahu cara menyelamatkan diri," kata Safrizal kepada kami di rumahnya di Banda Aceh, Sabtu, 16 November 2024.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Heyder Affan
Semestinya mereka yang tinggal di zona berbahaya mengetahui secara persis apa yang harus dilakukan ketika ada tsunami.
"Misalnya dia harus tahu tindakan evakuasi dan rute-rute evakuasi," ujarnya.
"Dan sudah tertanam dalam pikirannya kalau terjadi bencana, kemana saya harus menuju."
Masalahnya sekarang, bagaimana masyarakat dapat merawat ingatan bencana agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan jika bencana datang?
Jawaban Safrizal: "Kemampuan mitigasi ini harus diujikan, harus disimulasikan, harus didrill."
Seperti apa kesiapan warga 'desa tangguh bencana'?
Saat kami berada di Aceh pada pertengahan November 2024 lalu, UNESCO menggelar simulasi evakuasi tsunami.
Mereka menggelar di sejumlah tempat di Banda Aceh dan Aceh Besar. Acara ini melibatkan siswa sekolah hingga masyarakat biasa.
Salah-satu simulasi itu digelar di Gampong Lam Kruet, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Heyder Affan
Dua gampong ini dipilih, karena mereka meraih sertifikat dari UNESCO sebagai daerah siaga tsunami(tsunami ready).
Kami mendatangi gampong Lam Kruet pada Rabu, 13 November 2024, dan bertemu dua warga di sana.
Nur Hayatun, kelahiran 1972, sudah mengetahui bahwa desanya mendapat status daerah siaga tsunami.
"Kami juga ikut simulasi tadi di kantor camat," kata ibu empat anak ini.
Sebelumnya dia juga beberapa kali ikut acara serupa.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Heyder Affan
Salah-satu materi yang selalu diingatnya, yaitu jangan gampang panik.
"Lalu sebisa mungkin lari ke gunung, atau daerah yang lebih tinggi."
"Demikian pula, kalau habis gempa, lalu air laut surut, jangan ke sana," ungkap Nur Hayatun.
Menurutnya, simulasi seperti ini penting karena membuat dirinya menjadi ingat apa yang mesti dilalukan jika bencana datang.
"Dan saya selalu ingatkan ke anak-anak, kalau ada bencana, jangan panik dan lain-lain."
Nur Hayatun sudah tinggal sekitar 18 tahun di Lam Kreut. Dia membuka warung sederhana di salah-satu sudut desa itu.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Heyder Affan
Di sebelah warungnya, berdiri pula kios minuman buah yang dikelola Hasna, kelahiran 1977.
Suami Hasna adalah warga Lam Kreut. Dia sendiri berasal dari Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga.
Hasna mengaku belum pernah ikut simulasi tsunami.
"Saya belum pernah diajak," akunya.
Dia juga harus menjaga warungnya mulai pagi sampai malam.
"Tapi saya paham kalau ada tsunami, harus lari ke gunung," ujarnya.
Ini didasarkan pengalaman warga gampong Nusa saat tsunami 2004.
Di desanya, korban meninggal dunia relatif sedikit, yaitu 10 orang.
"Saat itu ada bule yang kasih tahu, ada air laut naik, dan kita diminta lari ke gunung," kata ibu dua anak ini.

Sumber gambar, Getty Images/Seth C.Peterson
Bagaimanapun, seperti pernah diakui oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh itu masih kekurangan desa tangguh bencana.
Sampai 2019 lalu, dari 90 desa di Banda Aceh, baru ada lima desa tangguh bencana.
Di antaranya Gampong Deah Glumpang, Gampong Jawa, Gampong Pande, serta Gampong Lampulo.
Tapi apa indikator sebuah desa dapat memenuhi syarat sebagai desa tangguh bencana?
- Pertama, memiliki kemampuan menghadapi bencana
- Kedua, mampu memulihkan diri setelah bencana
- Ketiga, memiliki regulasi penanggulangan bencana
- Keempat, memiliki peta bencana seperti jalur evakuasi ketika ada bencana
- Kelima, memiliki rencana penanggulangan bencana berkelanjutan
'Jangan sampai sepeda motor kosong bensin'
Kita kembali lagi ke sosok Agustina Dewi dan Mak Dek.
Tinggal tidak jauh dari bibir pantai, bahkan rumah Mak Dek jaraknya tidak sampai 50 meter, apakah mereka sudah 'siap' jika tsunami terjadi lagi?
"Kita sudah pengalaman," kata Dewi.
"Pengalaman itu mengajar [kita] untuk ke depan."
Dahulu, saat ada gempa besar di Aceh, Dewi dan suaminya lari kalang kabut menjauhi laut.
Dia teringat saat itu meminta tumpangan kepada tetangganya yang naik sepeda motor, tapi ditolak.
Dari pengalaman 'ditolak' inilah, sehari setelah gempa itu, Dewi dan suaminya memutuskan "beli sepeda motor bekas".
Dia lalu memberikan contoh lain yang paling sederhana: jangan sampai sepeda motor kosong bensinnya.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Dwiki Marta
Lainnya? "Jangan panik."
Kepada kami, Dewi kemudian secara panjang lebar memaparkan kira-kira ke arah jalan mana nanti motornya melaju.
Dia juga memperkirakan jalan mana yang tidak boleh dilalui. "Saya sudah wanti-wanti ke suami, jangan lewat jalan itu, pasti macet."
Dewi yakin betul para tetangganya di Ulee Lheue juga sudah siap apabila bencana itu datang. Apalagi mereka sering ikut simulasi tsunami.
"Insya Allah, kita sudah siap. Kalau istilah saya: Kita sudah enggak takut lagi tinggal di pantai.
Ini adalah seri kedua dari tiga seri liputan khusus peringatan 20 tahun gempa dan tsunami Aceh.
Seri pertama, Kisah 'bocah ajaib' Martunis Ronaldo bertahan hidup selama 21 hari – 'Saya dikelilingi mayat dan dikira hantu' bisa Anda simak di laman BBC News Indonesia.
Dan seri ketiga, 'Hikmah terbesar dari tsunami adalah perdamaian Indonesia-GAM' dapat juga Anda baca di laman BBC News Indonesia.























