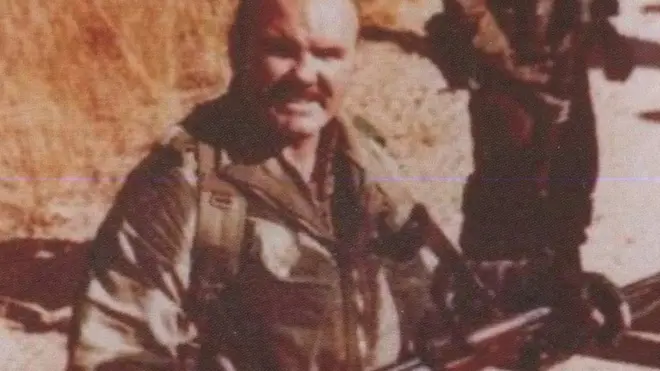The Mauritanian: 'penggambaran manusiawi' tahanan Muslim di penjara teroris AS

Sumber gambar, Elevation Pictures
- Penulis, Hanna Flint
- Peranan, Pemerhati film, BBC Culture
The Mauritanian adalah film terbaru yang menggambarkan pengalaman brutal tahanan di penjara milik pemerintah Amerika Serikat, di Teluk Guantanamo, Kuba. Apakah film ini akan menjadi yang paling berpengaruh?
Ketika Tahar Rahim ditawari untuk membintangi The Mauritanian, dia tidak banyak tahu tentang kamp tahanan AS itu, seperti halnya para penonton di Barat yang menjadi target penonton film tersebut.
The Mauritanianadalah biopik sutradara Kevin Macdonald tentang seorang pria bernama Mohamed Oud Slahi. Dia ditahan di Teluk Guantanamo selama 14 tahun tanpa dakwaan melakukan kejahatan apapun.
Rahim pernah mendengar berita tentang Markas Angkatan Laut di Kuba, tempat para penjaganya dilaporkan menganiaya tahanan. Namun sejujurnya, dia tidak bisa membayangkan bahwa "negara seperti AS akan membiarkan tentaranya memperlakukan manusia 'sampai sebegitunya'."
Namun setelah setuju untuk tampil di film tersebut, yang diadaptasi dari memoar Slahi, Guantanamo Diary, sang aktor berdarah Prancis-Aljazair melakukan riset. Semua pemahamannya pun berubah.
"Saya baca naskahnya, saya baca bukunya, saya tonton film-film dokumenter dan saya bicara dengan Mohamedou jadi saya senang bisa mendapatkan peran ini," kata Rahim kepada BBC Culture.
"Tapi saya sedih dan marah karena saya tahu ini adalah kisah nyata," tuturnya.
Sebelum peristiwa 11 September, representasi Teluk Guantanamo di layar lebar yang paling terkenal adalah film tahun 1992, A Few Good Men.
Diadaptasi oleh Aaron Sorkin dari drama panggung berjudul sama, film drama hukum itu dibintangi Tom Cruise, Demi Moore, dan Kevin Bacon sebagai pengacara militer yang menangani kasus pembunuhan seorang tentara di markas tersebut.
Pada 2002, Presiden George W. Bush menetapkan Teluk Guantanamo sebagai pusat penahanan untuk teroris Muslim yang diyakini terlibat dalam serangan 11 September.
Sejak itu, lokasi yang dijuluki 'Gitmo' menjadi topik perdebatan sengit tentang kekuatan militer AS dan siasat pemerintahan negara itu membenarkan kebijakan mereka.
Berbagai film dan siaran televisi lain menggambarkan Penjara Teluk Guantanamo dan kengerian yang terjadi di dalamnya. Beberapa di antara film itu, seperti Camp X-Ray (2014) dan The Report (2019), berfokus pada perspektif "kulit putih" warga AS. Hal ini menciptakan kesenjangan empati antara subyek film dan penonton, yang memicu hambatan memahami trauma yang diperlihatkan.
Daphne Eviatar, Direktur Hak Asasi Manusia di Amnesty International AS, menyebut narasi film-film seperti ini seringkali gagal menggambarkan para tahanan sebagai manusia.
"Sulit untuk menyediakan cukup konteks dan pemahaman tentang kehidupan mereka sehari-hari ketika cerita mereka itu hanyalah bagian latar belakang dari film berdurasi satu-dua jam," kata Eviatar kepada BBC Culture.
Sekitar 40 orang masih ditahan penjara itu hingga waktu yang belum ditentukan. Kebanyakan warga AS sama sekali tidak tahu siapa orang-orang ini dan tidak paham tentang tempat dan budaya asal mereka atau bagaimana mereka bisa ditangkap dan diserahkan ke otoritas AS untuk tujuan politik atau korup.
"Selain menempatkan orang-orang ini di luar jangkauan hukum AS, memenjarakan mereka di Guantanamo menempatkan mereka di luar jangkauan imajinasi AS."

Sumber gambar, Graham Bartholomew/Elevation Pictures
Masalah 'penyelamat berkulit putih'
Dengan menampilkan para tentara dan pengacara AS secara simpatik sebagai orang-orang yang berusaha menolong para tahanan, Camp X-Ray dan The Report juga dapat dilihat sebagai bagian dari tradisi yang disebut 'white saviour'.
Ini adalah narasi yang berfokus pada protagonis kulit putih yang datang untuk menolong orang kulit berwarna, serta lebih menitikberatkan pada hal yang utama ketimbang yang lainnya.
Cerita-cerita ini dapat menjadi cara untuk membebaskan penonton kulit putih dari rasa bersalah. Di sisi lain, narasi ini dapat membujuk penonton kulit putih membeli tiket film tentang kelompok orang yang kemungkinan besar nyaris tak pernah mereka temui.
The Mauritanian juga mengikuti narasi ini, tapi tidak sepenuhnya. Meskipun berfokus pada perjalanan mengerikan Slahi dari kampung halamannya di Mauritania, tempat dia ditangkap dua bulan setelah 11 September dan dituduh bekerja untuk al-Qaeda, film ini juga memberi cukup ruang bagi peradilan AS, baik pihak yang membelanya maupun melawannya atas nama keadilan.
Jodie Foster berperan sebagai pengacara Nancy Hollander. Dia memperjuangkan kebebasan Slahi. Aktor Benedict Cumberbatch bermain sebagai pengacara militer, Letkol Stuart Couch, yang mengajukan hukuman mati terhadap Slahi, sampai bukti baru muncul.
Namun kendati para aktor tersebut turut menyumbangkan kebintangan dalam film ini, mereka ingin membatasi waktu mereka tampil di layar, kata produser itu, Michael Carlin.
"Biasanya aktor berusaha membuat peran mereka lebih besar, tapi dalam kasus ini, yang terjadi hampir sebaliknya," kata Carlin kepada BBC Culture.
"Mereka tidak mau melakukan apapun yang akan mengalihkan dari cerita Mohamedou karena itulah alasan mereka membuat film ini. Mereka tidak melakukannya untuk uang."

Sumber gambar, Graham Bartholomew/Elevation Pictures
Slahi dikenai tuduhan terorisme karena dia pernah mendukung al-Qaeda dalam pemberontakan di Afghanistan pada tahun 1980-an. Tapi setelah bertahun-tahun mengalami penyiksaan fisik dan psikologis di kamp tahanan tersebut, Hollander membantunya memenangkan keputusan penahanan secara tidak sah oleh pemerintah AS.
Slahi tidak pernah didakwa dengan kejahatan apapun, tetapi tetap dikurung selama enam tahun sebelum dibebaskan pada tahun 2016. Foster dan Cumberbatch tidak mau mencuri fokus dari penderitaannya.
Slahi mempercayai Macdonald tidak hanya karena latar belakangnya dalam pembuatan film dokumenter seperti Touching the Void (2003) dan Marley (2012) tapi karena pengalamannya di Afrika membuat biopik The Last King of Scotland, yang dicalonkan untuk Piala Oscar. Film itu dibintangi Forest Whittaker sebagai Presiden Uganda Idi Amin. "Film itu begitu meyakinkan," kata sang penulis.
The Mauritanian sangat mengandalkan Slahi untuk memberi otentisitas visual pada ceritanya, sebagaimana memoar Slahi menjadi dasar bagi naskahnya.
Sang mantan tahanan memberikan deskripsi rinci kepada Macdonald dan Carlin tentang penahanannya di Guantanamo. Dia menggunakan tubuhnya untuk menentukan ukuran pasti sel penjara dan kurungan tempat ia ditahan. Tujuannya, supaya para sinieas ini dapat mereplikasi kamp itu ke dalam set yang dibangun oleh teknisi militer di Cape Town, Afrika Selatan.
Dalam mereka ulang Guantanamo, tim produksi mengandalkan foto-foto dari kantor berita, gambar yang diunggah para tentara ke internet, dokumen militer serta manual yang dicarikan oleh konsultan militer. Walau begitu, Slahi boleh memilah mana informasi yang akurat mana yang tidak.
"Beberapa konsultan yang membantu kami di industri film terlalu condong pada militer, jadi informasi dari mereka tidak bisa ditelan mentah-mentah," kata Carlin.
"Namun Mohamedou dapat membantu saya untuk memilah semuanya sehingga kita tahu mana foto yang benar, mana yang tidak, dan mana yang cocok untuk ceritanya.
"Semua ini tentang perampasan hak dan itulah yang kami usahakan," ucapnya.

Sumber gambar, Elevation Pictures
Penggambaran yang manusiawi
Yang tidak diinginkan oleh tim kreatif film ini ialah menampilkan Slahi sebagai sesuatu yang kurang dari manusia.
The Mauritanian memang menunjukkan beberapa perlakuan kejam yang dia alami namun ketika penyiksaan mulai memasuki narasi, adegan berpindah ke ingatan Slahi tentang kehidupannya sebelum penahanan.
"Ketika Anda menyiksa suatu karakter, mereka menjadi tidak simpatik, yang sebenarnya aneh," kata Carlin.
"Tapi kami tidak mau membuat film yang menjual sadisme jadi Kevin dan para penulis naskah mengeluarkan Slahi dari ruang tahanan ketika hal-hal mengerikan terjadi dan membawanya ke masa lalu, supaya Anda tetap bisa melihat sosok ini sebagai manusia."
Rahim menghabiskan waktu bersama Slahi untuk memahami pengalamannya, serta mempelajari kepribadian dan tingkah lakunya, tetapi merasa "bodoh" dengan beberapa pertanyaan yang dia tanyakan.
"Saya berbicara tentang apa yang terjadi di sana dan melihat trauma di wajahnya dan saya jadi merasa tidak enak," kenang sang aktor.
"Saya merasa, saya tidak ingin melakukan ini, dia (Slahi) sudah terlalu lama menderita jadi saya berhenti dan mulai membicarakan hal-hal [lain] sehingga saya dapat mengenalnya karena kepribadiannya, cara dia bergerak, cara dia berbicara, cara dia menjawab pertanyaan, cara dia bercanda. Itu membantu saya menanamkan kepribadiannya ke dalam diri saya. "

Sumber gambar, Elevation Pictures
Rahim, yang terkenal dengan perannya dalam drama Prancis A Prophet (2009) dan miniseri tentang serangan 11 September The Looming Tower (2018), berusaha menghindari peran sebagai karakter teroris Muslim yang dibuat untuk film dan TV selama 20 tahun terakhir.
Tapi ketika membaca naskah untuk The Mauritanian, Rahim mendapati film tersebut adalah salah satu dari sedikit yang memiliki "karakter Muslim yang simpatik di jantung sebuah film Amerika," dan karena itu merasa diberdayakan dengan keikutsertaannya dalam proyek ini.
"Saya harus tahu bahwa Slahi tidak bersalah karena jika dia betul-betul seorang teroris, saya rasa saya tidak akan menerima peran ini," kata Rahim.
"Saya tidak bilang teroris itu tidak ada. Sebagian kecil dari orang-orang ini mengambil semua perhatian kita, dan kita bahkan tidak melihat orang-orang yang lain dan bagaimana mereka begitu menderita."
"Mohamedou Slahi memenangkan kasusnya, dia tidak bersalah dan film ini adalah kesaksian untuk generasi berikutnya," kata Rahim.
"Saya tidak peduli apakah sutradaranya berkulit putih atau hitam atau Asia. Film-film ini perlu diceritakan dan sejarah ini diperlihatkan kepada penonton, atau kita ditakdirkan untuk mengulanginya."

Sumber gambar, The Red Cross/CC BY-SA 3.0
'Pena lebih kuat dari pedang'
Slahi tidak ingin merasakan kembali momen-momen terburuk dari penahanannya sehingga dia tidak menonton adegan-adegan paling traumatis dalam film tersebut. Tapi, dengan bukunya diadaptasi menjadi film fitur yang terkenal, dia percaya itu adalah bukti nyata bahwa pena lebih kuat dari pedang.
"Saya tidak percaya pada kekerasan tetapi keseluruhan cerita saya adalah kekerasan terhadap tubuh saya, kepolosan saya, anggota keluarga saya, dan saya tidak pernah melakukan apa pun kepada AS," katanya. "Film saya adalah kemenangan tanpa kekerasan, ini adalah kemenangan pena."
Faktanya, meskipun banyak film layar lebar, dokumenter, acara TV, buku, dan laporan berita telah menunjukkan realitas di Penjara Guantanamo, kamp tersebut masih dibuka sampai sekarang.
Saata menjabat Presiden AS, Barack Obama berjanji untuk menutupnya tapi gagal. Sekarang, Presiden Joe Biden mengatakan dia menargetkan untuk menutupnya sebelum masa jabatan pertamanya selesai.
Jadi dengan presiden baru di Gedung Putih, mungkinkah The Mauritanian menjadi film tentang Guantanamo yang menandai akhir dari kamp tahanan tersebut?
Rahim ingin para penonton mendapatkan pesan harapan dan pengampunan alih-alih amarah.
Sementara itu, Eviatar dari Amnesty International berkata, "film apa pun yang menggambarkan tragedi Guantanamo, bagaimana banyak orang berakhir di sana dengan cara yang tidak adil dan seringkali serampangan, sehingga memberi tekanan kepada pemerintah AS untuk menutupnya, memberi jasa yang sangat besar."
Slahi, yang masih ditolak masuk ke AS dan Inggris lima tahun setelah dibebaskan dari Teluk Guantanamo tanpa kompensasi atau permintaan maaf, berharap film ini akan menunjukkan kepada dunia Barat bahwa dia adalah orang yang tidak bersalah dan bahwa persepsi negatif terhadap orang Timur Tengah dan Afrika Utara harus diakhiri.
"Saya ingin orang-orang mengetahui cerita saya dari sisi saya dan saya merasa rendah hati karena cerita itu dibuat menjadi film besar," katanya.
"Saya tidak punya senjata, saya tidak punya polisi. Saya tidak punya drone untuk membunuh orang, tapi saya punya kata-kata dan saya ingin memperdebatkan eksepsionalisme negatif terhadap dunia Arab dan Afrika.
"Kami tidak boleh diculik; kami tidak boleh disiksa," kata Slahi.
---
Artikel ini pertama kali tayang dalam bahasa Inggris di BBC Culture, dalam judulExposing life inside the world's most notorious prison.