Kisah putri pewaris takhta Bhopal di India yang menentang stereotip perempuan Muslim

Sumber gambar, Shams Ur Rehman Alavi
- Penulis, Cherylann Mollan
- Peranan, BBC News, Mumbai
- Waktu membaca: 5 menit
Abida Sultan tak seperti tipikal putri kerajaan pada umumnya.
Dia memotong pendek rambutnya, berburu harimau, dan pemain polo yang handal.
Sejak masih berusia sembilan tahun, Abida bisa menerbangkan pesawat dan menyetir mobil Rolls-Royce.
Dia lahir pada 1913 dari keluarga ‘begum’ (perempuan Muslim terhormat) yang memerintah negara bagian Bhopal di India Britania selama lebih dari satu abad.
Abida meneruskan warisan mereka dalam hal menentang stereotip soal perempuan, khususnya perempuan Muslim.
Dia menolak mengenakan purdah—praktik yang mengharuskan perempuan-perempuan Muslim dan Hindu untuk mengenakan pakaian tertutup serta memisahkan diri dari laki-laki.
Abida menjadi pewaris takhta pada usia 15 tahun.
Dia menjalankan kabinet ayahnya selama lebih dari satu dekade, bergaul dengan para pejuang kemerdekaan terkemuka India, dan menyaksikan langsung kekerasan dan kebencian yang melingkupi negara ini setelah Pakistan memisahkan diri pada 1947.
Sejak kecil, dia sudah dipersiapkan untuk mengambil alih kekuasaan di bawah bimbingan neneknya, Sultan Jehan, sosok penguasa Bhopal dan dikenal tegas.
Dalam otobiografinya yang dirilis pada 2004, Memoirs of a Rebel Princess, Abida menceritakan bahwa dia harus bangun pada pukul empat pagi setiap hari untuk membaca Al-Qur'an.
Hari-harinya kemudian dilanjutkan dengan beragam kegiatan mulai dari belajar olahraga, musik, hingga berkuda.
Dia juga melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu dan membersihkan kamar mandi.
“Kami para perempuan tidak diperbolehkan merasa rendah diri karena jenis kelamin kami. Semuanya setara,” katanya dalam sebuah wawancara mengenai masa kecilnya.
“Kami punya semua kebebasan yang dimiliki anak laki-laki. Kami bisa berkuda, memanjat pohon, memainkan permainan apa pun yang kami inginkan. Tidak ada batasan”.
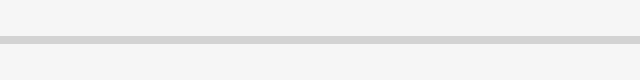
BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.
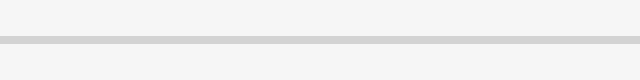
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Abida memiliki karakter tangguh dan mandiri bahkan sejak masih kanak-kanak.
Ketika berusia 13 tahun, dia membangkang perintah neneknya yang memaksanya menjalankan purdah.
Dengan keberaniannya ditambah dukungan pemikiran ayahnya yang terbuka, dia berhasil berkelit dari praktik tersebut semasa hidupnya.
Sebagai seorang pewaris tahta di Bhopal, Abida punya peluang dijodohkan dengan pewaris tahta dari negara bagian lain.
Pada usia 12 tahun, dia dinikahkan dengan Sarwar Ali Khan, teman masa kecilnya yang berasal dari keluarga kerajaan di negara bagian tetangga, Kurwai.
Dia juga menceritakan bagaimana pernikahan itu terjadi.
Suatu hari, ketika sedang bermain perang bantal dengan sepupunya, neneknya tiba-tiba masuk ke kamar dan memintanya berdandan untuk menghadiri pernikahan.
Hanya saja, tidak ada yang memberi tahu bahwa dia lah pengantinnya.
“Tidak ada yang mempersiapkan atau memberi tahu saya bagaimana saya harus bersikap,” tulisnya.
“Saya masuk ke kamar nikah, mendorong perempuan-perempuan yang berkerumun agar menyingkir, wajah saya terlihat, cemberut seperti biasa karena lagi-lagi dipilih untuk sebuah eksperimen baru,” kata Abida.
Prosesi itu berjalan singkat, sama seperti umur pernikahannya yang hanya bertahan kurang dari satu dekade.

Sumber gambar, Shams Ur Rehman Alavi
Abida kemudian merasakan peliknya pernikahan. Bukan semata karena usianya yang masih muda, tapi juga karena didikannya yang ketat dan saleh.
Dia terang-terangan menceritakan bagaimana minimnya pengetahuan dan ketidaknyamanan soal seks mempengaruhi hubungan pernikahannya.
“Setelah menikah, saya langsung mengalami trauma suami-istri.”
“Saya tidak menyadari bahwa hubungan intim akan membuat saya begitu ngeri, mati rasa dan merasa tidak suci,” tulisnya sambil menambahkan bahwa dia tidak pernah bisa ‘menerima hubungan suami-istri’.
Kondisi ini menyebabkan kehancuran pernikahannya.
Sejarawan Siobhan Lambert-Hurley—dalam makalahnya tentang keintiman dan seksualitas dalam tulisan-tulisan otobiografi perempuan-perempuan Muslim di Asia Selatan—menggarisbawahi bagaimana refleksi jujur Abida soal keintiman seksual dengan suaminya meruntuhkan stereotip bahwa perempuan Muslim tidak menulis tentang seks.
Abida bersuara secara lugas dan terbuka membahas relasi seksualnya.
Baca juga:
Setelah pernikahannya berantakan, Abida meninggalkan di Kurwai lalu kembali ke Bhopal.
Tetapi putra tunggalnya dari pernikahan ini, Shahryar Mohammad Khan, menjadi korban konflik hak asuh yang buruk dan berlarut-larut.
Abida, yang merasa frustasi dan tak ingin berpisah dengan putranya, mengambil langkah berani untuk membuat suaminya mundur.
Suatu malam pada Maret 1935, dia berkendara selama tiga jam ke rumah suaminya di Kurwai.
Dia memasuki kamar tidurnya, mengeluarkan pistol, melemparkannya ke pangkuan suaminya dan berkata: “Tembak saya atau saya akan menembakmu.”
Insiden itu, ditambah dengan perkelahian fisik yang dimenangkan Abida, mengakhiri sengketa hak asuh itu.
Dia kemudian membesarkan putranya sebagai ibu tunggal sambil menjalankan tugasnya sebagai pewaris takhta.
Abida menjalankan kabinet negaranya dari 1935 hingga 1949, ketika Bhopal digabung dengan negara bagian Madhya Pradesh di India.
Dia juga menghadiri konferensi meja bundar—yang digelar pemerintah Inggris untuk menentukan pemerintahan masa depan India.
Di sana dia bertemu dengan para pemimpin berpengaruh seperti Gandhi, Motilal Nehru dan putranya, Jawaharlal Nehru, yang kemudian menjadi perdana menteri pertama India.
Pada 1947, dia mengalami langsung masa-masa memburuknya hubungan antara umat Hindu dan Muslim serta kekerasan yang terjadi setelah Pakistan memisahkan diri.

Sumber gambar, Shams Ur Rehman Alavi
Dalam memoarnya, Abida menceritakan diskriminasi yang dia hadapi di Bhopal; bagaimana keluarganya yang telah tinggal di sana dengan damai selama beberapa generasi mulai diperlakukan sebagai “orang luar”.
Lalu dalam salah satu wawancara, Abida mengungkap kenangan mengerikan yang dia saksikan soal kekerasan antara umat Hindu dan Muslim.
Suatu hari, setelah pemerintah India memberitahunya bahwa sebuah kereta api yang membawa pengungsi Muslim akan tiba di Bhopal, dia pergi ke stasiun kereta api untuk mengawasi kedatangannya.
“Ketika kompartemen dibuka, mereka semua sudah mati,” katanya.
Kekerasan dan rasa tidak percaya inilah yang mendorongnya untuk pindah ke Pakistan pada tahun 1950.
Abida pergi diam-diam, hanya membawa putranya dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah.
Di Pakistan, dia memperjuangkan demokrasi dan hak-hak perempuan lewat jalur politik.
Abida meninggal dunia di Karachi pada tahun 2002.
Di Bhopal, selepas dia pergi ke Pakistan, pemerintah India menjadikan saudara perempuannya sebagai pewaris takhta.
Namun sosok Abida masih dikenal di negara bagian ini. Orang-orang memanggilnya dengan julukan “bia huzoor”.
“Politik agama selama beberapa tahun terakhir telah mengikis warisannya dan dia tidak lagi sering dibicarakan,” kata jurnalis Shams Ur Rehman Alavi, yang telah meneliti para penguasa perempuan Bhopal.
“Tetapi namanya tidak akan dilupakan secepat itu.”









