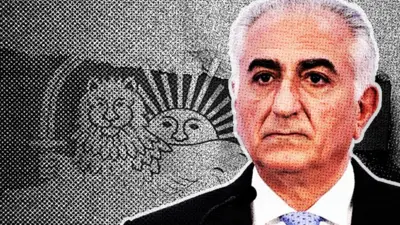Mengapa ketimpangan gender dan seksisme di Jepang sulit diatasi?

Sumber gambar, Getty Images
- Penulis, Mariko Oi
- Peranan, BBC News, Japan
Sebuah petisi menuntut pertanggungjawaban Ketua Olimpiade Tokyo 2020 atas perkataan seksisnya digagas mahasiswi berusia 23 tahun bernama Momoko Nojo.
Petisi itu dibuat Nojo, Februari lalu, sehari setelah orang nomor satu di lembaga penyelenggara Olimpade Tokyo, Yoshiro Mori, melecehkan perempuan secara verbal.
"Tujuan petisi itu bukan agar dia mengundurkan diri dari jabatannya," kata Nojo. Dalam 10 hari, petisi yang turut digagas 10 perempuan lainnya itu diteken lebih dari 100.000 orang.
"Saya merasa perlu melakukan sesuatu karena sampai sekarang, sebagai sebuah entitas masyarakat, perempuan Jepang masih harus menghadapi pelecehan seperti itu," ujarnya.
Yoshiro Mori adalah mantan perdana menteri Jepang yang kini berusia 83 tahun. Pada pertemuan Komite Olimpiade, dia berkata bahwa perempuan terlalu banyak bicara.
Satu pekan usai mengeluarkan pernyataan itu, Mori mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Olimpiade Jepang.
Ketika media massa melaporkan bahwa Mori memilih laki-laki lain yang juga berusia 80-an tahun sebagai penggantinya, banyak perempuan muda menuntut suksesi yang transparan.
Tuntutan itu berakhir dengan penunjukan Seiko Hashimoto, eks menteri urusan olimpiade. Dia adalah perempuan yang jauh lebih muda dari Mori.
Penunjukan Hashimoto dipandang sebuah kemenangan bagi perempuan. Namun Nojo, yang memimpin kelompok orang muda bernama No Youth No Japan, menilai pengunduran diri Mori solusi komprehensif untuk ketimpangan gender di Jepang.
"Banyak perusahaan mengecam pernyataan Mori, tapi beberapa dari mereka memiliki kurang dari 1% anggota direksi perempuan. Itu perlu diubah," kata Nojo.
Risa Kamio, anggota Dewan Kota Setagaya di Tokyo, sependapat dengan Nojo.
"Bagi saya, persoalan Mori hanyalah puncak gunung es. Itu seperti permainan memukul tikus tanah. Orang-orang mengkritiknya karena dia mencuat untuk dikecam, tapi sebenarntya ada banyak 'tikus-tikus' lainnya," kata Kamio.

Sumber gambar, MOMOKO NOJO
Permasalahan kesetaraan gender terus menjadi berita utama di Jepang.
Hanya beberapa hari setelah Mori mundur, partai politik yang menguasai pemerintahan Jepang, yaitu Partai Demokratik Liberal (LDP), mengizinkan anggota perempuan mereka menghadiri rapat internal yang dikhususkan untuk kader laki-laki.
Walau begitu, LDP tidak memberi para politikus perempuan itu hak berbicara di dalam forum partai.
Beberapa kasus yang melibatkan figur publik ini terjadi di tengah kebijakan Jepang untuk menggenjot representasi perempuan dalam masyarakat. Tahun 2015, Jepang mematok target ambisius agar perempuan dapat memegang 30% posisi kepemimpinan di Jepang pada tahun 2020.
Kasus ini juga bertepatan dengan peringkat Jepang yang terus-menerus turun dalam daftar negara dengan kesetaraan gender terbaik.
Forum Ekonomi Dunia menyebut kesenjangan gender di Jepang sebagai yang paling parah di antara negara-negara maju.
Seperti yang ditunjukkan Nojo, ada beberapa aktivisme di kalangan anak muda Jepang. Namun statistik menunjukkan, kebanyakan orang di negara itu menilai perbaikan urusan kesetaraan gender membutuhkan waktu lama.
Pertanyaannya, apa yang memicu situasi ini? Dan mengapa Jepang tidak membuat kemajuan yang berarti dalam kesetaraan gender?
'Beban pada perempuan'
Salah satu faktor utama pemicu situasi ini adalah peran tradisional laki-laki dan perempuan yang masih bertahan. Secara signifikan, cara pandang itu membatasi akses perempuan menjadi pemimpin.
"Secara historis, setelah Perang Dunia II, para suami didorong menjadi pekerja keras yang mengabdikan kehidupan untuk perusahaan sementara para ibu untuk tinggal di rumah," kata Hiroki Komazaki, pendiri dan CEO Florence.
Florence adalah organisasi nirlaba yang mengadvokasi para orang tua yang bekerja.
Dorongan puluhan tahun itu melahirkan sebuah norma: suami bekerja dalam waktu yang sangat lama, sedangkan pekerjaan rumah, termasuk mengasuh anak, masih menjadi tanggung jawab utama para istri.
Survei terbaru dalam skala nasional di Jepang pada tahun 2020 menunjukkan, para ibu masih melakukan pekerjaan rumah 3,6 kali lebih banyak daripada ayah.
Karena norma semacam ini, serta bias dalam perekrutan pegawai di beberapa perusahaan dan budaya kerja yang resisten terhadap perubahan, banyak perempuan berhenti bekerja setelah memiliki anak.
Situasi itu juga memaksa banyak perempuan memilih pekerjaan paruh waktu atau kontrak kerja yang tidak memberi mereka peluang mendapatkan promosi jabatan.

Sumber gambar, Getty Images/SOPA Images
Pembagian kerja yang mengakar ini berdampak pada pertumbuhan populasi. Sejumlah perempuan memiliki lebih sedikit anak atau bahkan tidak memilikinya sama sekali saat menghadapi risiko berhenti bekerja atau keluar dari jalur karier apabila memiliki anak.
Angka kelahiran di Jepang saat ini berada pada rekor terendah. Tingkat pernikahannya juga merosot, salah satunya karena laki-laki cemas tidak dapat menghidupi keluarga hanya dengan mengandalkan gaji.
Namun karena krisis demografi ini sudah berdampak, pemerintah Jepang ingin lebih banyak perempuan memiliki anak tapi juga tetap bekerja. Ini mereka anggap dapat menopang angkatan kerja yang menyusut.
Di situlah peran Womenomics, teminologi untuk serangkaian kebijakan yang diluncurkan tahun 2015 oleh Perdana Menteri Jepang kala itu, Shinzo Abe.
Abe berjanji menciptakan masyarakat di mana perempuan bisa "bersinar". Dia juga mengklaim akan meningkatkan peluang perempuan menuju pucuk kepemimpinan.
Namun para kritikus menilai kebijakan itu lebih mendorong perempuan kembali ke tempat kerja demi menggenjot perekonomian. Womenomics dianggap bukan solusi persoalan seperti minimnya layanan pengasuhan anak.
"Jepang tidak mendorong kesetaraan gender," kata jurnalis Toko Shirakawa, yang kerap menulis isu penurunan angka kelahiran di negara tersebut.
"Pemerintah hanya mendorong agar jumlah pemimpin perempuan bertambah, tapi tidak menawarkan perubahan atau dukungan yang mendasar. Beban itu harus ditanggung perempuan," ujarnya.
Artinya, hanya sedikit perubahan yang terjadi di Jepang. Pada laporan Kesenjangan Gender Global tahun 2021 yang disusun Forum Ekonomi Dunia, Jepang duduk di peringkat ke-120 dari 156 negara dalam hal kesetaraan gender. Sejak 2006, mereka turun 40 peringkat.

Sumber gambar, Getty Images
Meski lebih banyak wanita akhirnya benar-benar bergabung dengan angkatan kerja, banyak dari mereka tetap bekerja paruh waktu atau tanpa peluang promosi jabatan.
Pekerjaan seperti itu tidak memungkinkan mereka naik ke posisi pimpinan.
Di sektor swasta, jumlah manajer perempuan naik 7,8% pada tahun 2019, tapi itu masih jauh dari target 30%, yang pencapaiannya diam-diam diperpanjang pemerintah Jepang hingga tahun 2030.
Di bidang politik, jumlah anggota legislatif perempuan hanya 9,9% dari total anggota di majelis rendah parlemen. Persentase itu menempatkan Jepang di peringkat ke-166 dari 193 negara.
Konsekuensi dari kondisi ini, laki-laki masih mendominasi bisnis dan kepemimpinan politik di Jepang.
Pengambilan kebijakan yang mengadvokasi kepentingan perempuan berjalan lambat. Bahkan di beberapa wilayah Jepang, kebencian terhadap perempuan terus berkembang.
Mengapa orang Jepang tidak membicarakan isu ini?
Salah satu alasan berbagai pernyataan seksis seperti yang diutarakan Mori tidak digugat publik Jepang adalah etiket masyarakat yang tidak terucapkan, bahwa orang Jepang tidak saling bertengkar, terutama dengan orang yang lebih tua.
"Jepang adalah negara di mana orang merasa sulit untuk berbicara tanpa memandang usia atau jenis kelamin Anda," kata Nojo, yang petisinya turut memaksa Mori mundur dari Komite Olimpiade.
"Jika Anda angkat bicara, Anda bisa dianggap egois," ujarnya.
Ini adalah tradisi orang Jepang untuk "membaca udara" atau yang dalam bahasa lokal disebut kuuki o yomu.
Meskipun Anda menemukan perkataan seseorang yang seksis, banyak orang memilih tidak berkonfrontasi dengan masalah itu agar mencegah kecanggungan.
Kebiasaan itu memungkinkan Mori dan banyak orang sepertinya menganggap ucapan seksis mereka dapat diterima.
Bahkan pada masa lalu, jika dikritik mereka dapat meminta maaf dan memohon simpati publik dengan berkata, "Istri saya atau putri saya menyuruh saya mundur.
Ini persis yang dilakukan Mori. Dan setelahnya mereka lolos begitu saja.
Itulah sebabnya banyak perempuan lansia mendukung petisi yang dibuat Nojo. Banyak dari mereka merasa bertanggung jawab karena tidak bersuara di masa lalu.
"Saya ingin mengatakan dengan lantang bahwa tidak hanya perempuan Jepang yang marah dengan perkataan seksis itu," kata Komazaki.
"Mayoritas laki-laki, termasuk anggota parlemen, menganggap pernyataan dan tindakan seksis yang dilakukan oleh Mori dan Partai LDP ini tidak terpikirkan."
Menurut Komazaki, pergantian generasi akan menjadi faktor kunci mengikis kebiasaan ini.
Beberapa laki-laki tua telah memperbarui sikap melalui interaksi dengan cucu atau kolega yang lebih muda. Mereka mulai menyadari bahwa sikap dan persepsi yang dapat diterima seputar gender telah berubah.
'Satu orang tidak bisa bertarung sendirian'
Saat banyak orang mulai memperbarui sikap, media sosial menawarkan platform bagi generasi muda untuk menyuarakan pendapat. Lewat medium ini, ketidaksetujuan mereka dapat dianggap serius oleh para pemangku kepentingan, seperti sponsor Olimpiade dalam kasus Yoshiro Mori.
Namun tekanan dari orang-orang muda perlu diperkuat dengan kebijakan baru dan pesan dari para pemimpin Jepang.

Sumber gambar, Getty Images/SOPA Images
Untuk menghasilkan narasi itu, penting untuk memperbanyak perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik, kata Shirakawa.
"Kita perlu menetapkan batas minimal untuk meningkatkan jumlah calen anggota parlemen perempuan.
"Kita harus berpikir bahwa kuota 50:50 adalah keharusan dan mencari tahu apa yang menghalangi, bukan alasan mengapa Jepang tidak bisa mencapainya," ujarnya.
Shirakawa menilai beberapa perubahan bisa sangat efektif, salah satunya mengizinkan anggota parlemen mengikuti pemungutan suara untuk sebuah kebijakan dari jarak jauh.
Perubahan lainnya, kata dia, bisa berupa kesempatan agar anggota legislatif dapat mengasuh anak di parlemen.
Shirakawa juga mendukung penetapan batas minimal anggota per gender di parlemen.
"Di mana dan kapan pun, politikus laki laki berpengaruh harus mengusung politikus perempuan untuk memimpin komisi," ujarnya.
Shirakawa mencontohkan Rie Hirakawa yang ditunjuk menjadi pengawas Dewan Pendidikan Prefektur Hiroshima. Hirakawa disebut telah membuat banyak perubahan, antara lain menguji program baru demi pembelajaran yang lebih interaktif.
Hirakawa dalam tiga tahun terakhir juga bertindak cepat dengan bersiasat menjalankan pembelajaran jarak jauh saat wilayah lain di Jepang mengalami kesulitan.
Risa Kamio, anggota dewan lokal di Kota Setagaya di Tokyo, setuju bahwa perempuan perlu lebih terwakili di bidang politik.
"Satu orang tidak bisa bertarung sendirian. Saya menyadari bahwa semakin banyak anggota parlemen perempuan yang kita miliki, semakin banyak dari kita yang akan angkat bicara," kata Kamio.
Dia memutuskan untuk mencalonkan diri setelah kembali dari luar negeri pada tahun 2016. Dia ingin aspirasi para orang tua yang bekerja didengar.
Tapi Kamio menghadapi jalan terjal. Sejak awal, dia berjuang menemukan tempat pengasuhan anak untuk putranya yang saat itu berusia tiga tahun.
Ketika berkampanye, Kamio disuruh berdiri di luar stasiun lokal dari pukul 06.00 hingga tengah malam, untuk memperkenalkan wajahnya kepada warga di sana. Keharusan itu menyulitkannya berbagi waktu dengan keluarga.
Dan sekarang Kamio masih harus berurusan dengan struktur kerja yang ditujukan untuk laki-laki yang tampak mengesampingkan peran mereka dalam rumah tangga.
"Salah satu pertemuan dijadwalkan dimulai siang hari dan kami diberitahu untuk mengosongkan aktivitas sampai tengah malam," katanya.
"Sistem ini sangat tidak mempertimbangkan para ibu yang bekerja."
Dan walau suami Kamio mendukung pilihannya mencalonkan diri, sejumlah kerabat lainnya justru prihatin.
"Orang tua saya khawatir, terutama ibu saya yang sangat keberatan," kata Kamio, yang ibunya merupakan ibu yang tinggal di rumah.
"Ibu khawatir aku akan menjadi begitu sibuk sehingga aku akan mengabaikan putraku," tuturnya.
Harapan masyarakat dan tekanan tempat kerja seperti ini berdampak pada perempuan yang mempertimbangkan untuk menantang status quo di semua bidang.
Di satu sisi, kondisi itu juga mencegah banyak perempuan terlibat dalam pekerjaan.
Mako Tanaka, anggota No Youth No Japan, yakin perubahan yang lebih besar tentang bagaimana perempuan belajar dan memahami peran mereka dalam masyarakat diperlukan.
Perempuan berusia 20 tahun itu berkata, laki-laki dan perempuan diberikan pesan yang menekankan perbedaan mereka sejak usia dini.
"Di sekolah dasar, anak perempuan membawa tas merah, bukan tas hitam seperti anak laki-laki. Berulang kali, sedikit demi sedikit, kami diajari untuk menjadi rendah hati.
"Di Amerika Serikat, perempuan kuat dianggap keren. Di Jepang, kami diajari untuk patuh," kata Tanaka.
Jalan panjang di depan
Sampai perempuan angkat suara di semua sektor dan di semua tingkat masyarakat, tradisi misoginis tidak akan berakhir.
Namun, walau beberapa perusahaan mulai menciptakan tempat kerja yang lebih ramah untuk keluarga, jumlah perempuan masih sedikit.
Bahkan Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan, yang mempromosikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan, dituduh mempekerjakan pegawai dengan jam lembur berlebihan.
Beberapa pengamat menuduh perusahaan media, yang dengan cepat mengkritik komentar Mori, memiliki standar ganda berdasarkan jumlah anggota dewan redaksi perempuan.

Sumber gambar, Getty Images
Kamio tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Ini menunjukkan, meski ada beberapa perubahan, anak laki-laki dan perempuan masih dibesarkan secara berbeda.
"Sebagai ibu dari seorang anak laki-laki, saya terus mengingatkan diri saya sendiri betapa pentingnya membuatnya membantu pekerjaan rumah tangga," kata Kamio.
Namun Shirakawa menyebut paksaan agar Mori mundur merupakan kemajuan yang signifikan. Menurutnya, jika itu terjadi beberapa tahun lalu, Mori mungkin bisa meminta maaf tapi tetap mempertahankan pekerjaannya.
Dan tidak seperti generasi sebelumnya, Nojo dan Tanaka, dua perempuan berusia 20-an tahun, tidak peduli dengan dampak aktivisme mereka saat mencari pekerjaan.
Bahkan mereka belum siap untuk terjun ke dunia politik.
"Saya tahu seseorang harus melakukannya," kata Nojo. "Tapi saya tidak merasa senang jika menjadi politikus."
Nojo merasa terpengaruh oleh apa yang dilihatnya di arena politik dan menilai akan sulit berkembang di bidang itu.
Sementara itu, meski orang semakin berharap masalah kesetaraan gender ditangani, mereka merasa persoalan itu akan tuntas dalam waktu lama.
Kecenderungan itu muncul dalam survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian, Dentsu Institute.
Para responden survei itu memperkirakan, dibutuhkan waktu 24,7 tahun sebelum representasi perempuan mencapai 30% di manajemen perusahaan Jepang. Dan perlu 33,5 tahun sebelum perempuan menduduki setengah dari total kursi di parlemen Jepang.
Menggarisbawahi kemajuan yang lambat, akhir bulan lalu, pejabat tinggi Komite Olimpiade Jepang lainnya mundur setelah membuat pernyataan seksis.
Hiroshi Sasaki, Direktur Kreatif Komite Olimpade Jepang, berkata bahwa komedian Jepang bertubuh 'gemuk', Naomi Watanabe, pantas didandani seperti babi untuk upacara pembukaan ajang olahraga terbesar sejagat itu.
Sasaki bahkan menjuluki Watanabe dengan istilah "OlymPig".
Jalan Jepang menuju kesetaraan gender masih panjang.
---
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris di BBC Worklifedengan judulWhy Japan can't shake sexism.