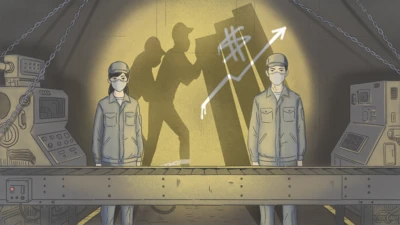'Bumerang buat diri sendiri dan serba salah’ – Apakah orang dengan HIV harus ungkap status saat periksa ke dokter gigi?

Sumber gambar, Getty Images
Periksa ke dokter gigi adalah hal yang biasa dilakukan banyak orang, namun bagi orang dengan HIV kunjungan ke klinik gigi kerap diwarnai dengan dilema karena stigma dan diskriminasi—bahkan dari petugas kesehatan—yang masih melekat.
Masih lekat dalam ingatan Winda Gunawan bagaimana raut muka dokter gigi yang memeriksanya sekitar setahun lalu berubah drastis begitu dia mengungkap status bahwa dirinya adalah orang dengan HIV (ODHIV).
Meski giginya sama sekali belum diperiksa, Winda langsung dirujuk ke rumah sakit oleh dokter tadi. Padahal, menurut Winda, dokter gigi itu sudah mengenakan sarung tangan.
Pekerja di salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi salah satu klinik gigi di Denpasar, Bali, sekitar Agustus 2023.
Bagi Winda—yang sudah memperoleh diagnosis HIV sejak 2018—penting untuk memberitahukan statusnya kepada tenaga kesehatan sebelum pemeriksaan gigi.
Winda rutin minum obat antiretroviral (ARV) untuk ‘menekan’ jumlah kopi virus HIV di tubuhnya. Sekarang, jumlah HIV di tubuhnya sudah mencapai status tidak terdeteksi.
Meski begitu, dia mengaku ingin para tenaga kesehatan mengetahui riwayat medisnya supaya mereka memberikan pelayanan yang terbaik.
Selain untuk kepentingan pengobatan, Winda juga ingin dokter dan perawat bisa lebih berhati-hati apabila ternyata dibutuhkan tindakan operasi.
“Lebih baik jujur supaya mereka bisa memberikan yang terbaik,” tutur Winda kepada wartawan Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Sumber gambar, Winda Gunawan
Winda bercerita bagaimana dokter gigi tadi langsung memberinya obat dan surat rujukan—tanpa sama sekali melihat giginya.
“Setahu saya kalau rujukan, harusnya pemeriksaan awal dulu?” curhat Winda.
Winda pun mengaku gundah karena ternyata keputusannya untuk membuka status HIV-nya malah menjadi “bumerang untuk diri sendiri.”
“Jadinya serba salah. Kalau tidak bilang, nanti kita tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang maksimal sesuai dengan rekam medis kita. Namun, ketika bilang, malah diginiin,” ujarnya.
Winda pun menceritakan pengalamannya ke teman-temannya sesama pekerja LSM dan mereka meyakinkan bahwa apa yang dia alami merupakan bentuk diskriminasi.
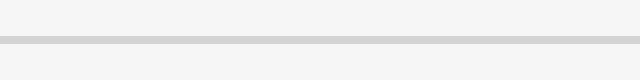
BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.
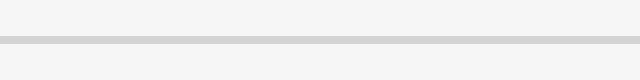
Sementara Anton, 35 tahun, pekerja swasta di Kerobokan, Badung, mengaku diberitahu oleh satu klinik gigi bahwa pasien dengan status HIV positif akan serta merta dirujuk ke rumah sakit.
“Sempat diinfokan [bahwa] memang pasti akan dilarikan ke rumah sakit kalau untuk yang statusnya positif. Alasannya, sih, biar ada penanganan yang lebih intensif,” ujar Anton, yang meminta nama lengkapnya tidak dipublikasikan.
Anton yang sebelumnya sempat tinggal di Jakarta mengaku merasa aneh mendengar informasi ini. Selama di ibu kota, tidak pernah sekalipun dia dirujuk meski sudah membuka status HIV-nya.
“Selama di Jakarta, aku enggak pernah mengalami seperti ini,” ujar Anton.

Sumber gambar, Getty Images
Stigma dan diskriminasi
Anton dan Winda tidaklah sendirian.
Puan Meirinda Sebayang, pendiri dan ketua Jaringan Indonesia Positif, mengatakan masih ada tenaga kesehatan yang menghindari kontak fisik dengan pasien ODHIV.
Selain itu, Puan mengatakan ada pula tenaga kesehatan yang mengambil tindakan pencegahan ekstra—misalnya memakai sarung tangan ganda—begitu mengetahui status HIV pasien.
“Atau menempatkan pasien HIV di akhir antrian untuk perawatan gigi,” ujar Puan.
Jaringan Indonesia Positif adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada dukungan dan advokasi untuk orang dengan HIV di Indonesia.
Tahun ini, Jaringan Indonesia Positif merilis studi Stigma Index 2.0 pada orang yang hidup dengan HIV.

Sumber gambar, Jaringan Indonesia Positif
Berdasarkan data yang dikumpulkan selama satu tahun sejak November 2022 hingga November 2023 di 16 provinsi di Indonesia, tercatat 15,9% ODHIV mengalami stigma dan diskriminasi dari tenaga kesehatan di pusat pelayanan kesehatan non-HIV—seperti poli gigi.
“Artinya, 15 dari 100 orang yang hidup dengan HIV pernah mengalami setidaknya satu bentuk stigma dan diskriminasi dari tenaga kesehatan di layanan non-HIV,” ujar Puan kepada BBC News Indonesia.
Puan menyebut data Jaringan Indonesia Positif ini sejalan dengan temuan studi Stigma dan Diskriminasi Terkait HIV di pelayanan-pelayanan kesehatan di Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Inovasi Kesehatan (PIKAT) pada 2024.
Data PIKAT menemukan 56,6% tenaga kesehatan memiliki sikap stigma terhadap orang dengan HIV—termasuk melakukan tindakan pencegahan yang tidak diperlukan.
“Salah satunya menggunakan sarung tangan ganda [yang] mencapai 27,1%,” ujarnya.
Selain itu, menurut data yang sama, sebanyak 59,2% petugas kesehatan juga cenderung memperlihatkan ekspresi kekhawatiran terkait HIV ketika melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi.
“Seperti [ketika] menyentuh pakaian, tempat tidur dan apa pun milik orang yang hidup dengan HIV,” ujar Puan.
Puan menilai stigma dan diskriminasi yang dialami para ODHIV ini dapat mempengaruhi kesehatan mereka.
“19,2% orang dengan HIV pernah menghentikan pengobatan ARV karena mengalami perlakuan stigma dan diskriminasi,” ujar Puan, mengutip studi Jaringan Indonesia Positif.

Sumber gambar, Getty Images
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Di Bandung, Jawa Barat, Doris Yondra Setiawan yang bekerja sebagai penyuluh di Yayasan Grapiks menyebut stigma dan diskriminasi dari petugas kesehatan seperti di klinik gigi terhadap ODHIV sebenarnya sudah menahun.
“Entah kenapa setahuku belum pernah masuk ke pembahasan nasional HIV. Padahal, kesehatan mulut dan gigi penting sekali. Harusnya dapat perhatian serius dari perhimpunan dokter gigi,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman Doris, memang ada juga dokter gigi yang bersikap biasa saja terhadap status HIV seseorang karena sudah mendapat pelatihan yang baik.
Bahkan, menurut dia, dokter-dokter gigi ini biasanya sudah menerapkan prosedur standar sterilisasi yang baik secara universal—sehingga mereka tidak masalah apabila pasien tidak mengungkapkan status HIV-nya atau bahkan tidak tahu bahwa dia positif HIV.
“[Namun] ada yang tidak suka [apabila] pasien tidak memberitahukan statusnya dari awal. Alasannya berarti menghalangi dokter memberikan pelayanan terbaik dengan berbohong soal status medis,” ujar Doris.
‘Perlu banyak pembekalan lebih lanjut’
Pertanyaan tentang apakah ODHIV perlu membuka statusnya ketika memeriksakan diri ke dokter gigi menuai tanggapan beragam di kalangan tenaga kesehatan.
Di Jakarta, dokter gigi Agam Ferry mengaku miris mendengar temuan-temuan Jaringan Indonesia Positif dan pengalaman negatif ODHIV ketika pergi berobat.
“Menghindari kontak fisik secara gamblang, menempatkan di posisi antrean tertentu, atau bahkan ruangan tertentu dengan prosedur standar tambahan seharusnya tidak pernah dibenarkan,” ujar Agam ketika dihubungi BBC News Indonesia.
“Perlu banyak pembekalan lebih lanjut terhadap nakes untuk memperbaiki 'paradigma' ini.”
Pria yang aktif di media sosial itu menekankan adanya prinsip kewaspadaan universal (universal precaution) yaitu “memperlakukan seluruh pasien seolah-olah [mereka] punya penyakit yang sangat menular”.

Sumber gambar, Getty Images
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tujuan utama dari kewaspadaan universal adalah untuk melindungi perawat dan pasien, serta mengurangi stigma.
Di sisi lain, penggunaan sarung tangan rangkap dua, menurut Agam, sebetulnya tidak termasuk ke dalam prosedur standar kewaspadaan universal.
“Kalau pertanyaannya [apakah sarung tangan ganda] dibutuhkan atau tidak [ketika menangani pasien ODHIV]... jika mengacu ke universal precaution, jawabannya: tidak,” tegas Agam.
“[Apalagi] untuk sebatas pemeriksaan standar atau rutin, tidak perlu memakai sarung tangan ganda. Saya beberapa kali kontrol pasien ODHIV dengan lesi rongga mulut di bangsal atau poli gigi selama pendidikan dokter gigi spesialis… saya tidak menggunakan sarung tangan ganda.”
Akan tetapi, Agam tak memungkiri bahwa dia kerap menemukan dokter gigi yang mengenakan sarung tangan ganda saat menangani ODHIV dengan beberapa alasan.
“Pertama, bidang kedokteran gigi berkaitan penggunaan alat tajam dan berputar yang rentan menyebabkan perlukaan,” kata Agam.
Kedua, menurutnya, standar sarung tangan untuk tenaga kesehatan yang digunakan di Indonesia tak sesuai standar keamanan internasional.
“Karenanya, dianggap perlu menggunakan sarung tangan ganda pada saat memerlukan tindakan invasif seperti bedah gigi impaksi atau implan.”
Meskipun begitu, Agam menekankan tetap saja ada ketentuan ketika seorang dokter gigi menggunakan sarung tangan dobel—misalnya, jangan secara sengaja memperlihatkan langsung di depan pasien saat mengenakannya.
“Saya rasa, alasan ini sifatnya personal. Karena secara general [umum], menjadi [tenaga kesehatan] harus siap dengan segala konsekuensinya,” ujar Agam.
“Saya sendiri masuk ke golongan [yang menganggap] status disclosure [membuka status] dari ODHIV itu hak penuh yang bersangkutan. Kalau ada yang memutuskan untuk mengungkapkan statusnya, saya anggap itu sebagai bonus buat saya,” terangnya.

Sumber gambar, AMAHL AZWAR
Berbeda dengan dokter gigi Agam, seksolog dokter Boyke Dian Nugraha termasuk yang mendukung ODHIV membuka statusnya ketika pergi berobat—termasuk ke klinik gigi.
“Saya lebih suka mereka open [terbuka] karena itu akan menyelamatkan banyak dokter OB-GYN [ginekolog], dokter gigi, dokter bedah ,” ujar Boyke.
Menanggapi soal kewaspadaan universal atau universal precaution, Boyke berpendapat pasien ODHIV memerlukan penanganan ekstra.
“Pasien HIV [prosedur standar]-nya lebih. [Misalnya] sarung tangannya dobel. Kemudian dia juga tidak boleh menyusui karena penularan HIV bisa dari air susu ibu,” papar Boyke.
“Bukan kita memberikan stigma, tapi memang protokol untuk melindungi tenaga kesehatan itu sendiri.”
Menempatkan ODHIV di nomor akhir antrian pun, menurut Boyke, juga tidak masalah selama pasien tersebut diberi penjelasan secara baik-baik bahwa ini dilakukan untuk menghindari penularan dari alat gigi, “meskipun alatnya steril”.
Dia lantas menjelaskan bahwa standar kesehatan di daerah tak bisa disamakan dengan di Jakarta kendati ada apa yang disebut sebagai “kewaspadaan universal”.
Boyke berpendapat jika sarung tangan ganda digunakan secara universal, penerapannya akan sulit lantaran dana yang dimiliki klinik atau puskesmas di daerah terbatas.
“Fasilitas di daerah jangan disamakan dengan di Jakarta atau di luar negeri yang semuanya serba steril,” jelasnya.
Di sisi lain, ada kalanya pasien tak menyadari statusnya adalah ODHIV karena tak pernah memeriksakan statusnya.
“Itu risiko jadi dokter,” kata dia.
Apa kata Kementerian Kesehatan?
Meskipun kalangan tenaga kesehatan berbeda pendapat, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa ODHIV tak diwajibkan untuk membuka status mereka saat pergi berobat.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengungkapkan bahwa mewajibkan pasien dengan HIV membuka statusnya tak hanya “menimbulkan masalah etis”, tapi juga berisiko “memperkuat stigma” terhadap orang dengan HIV.
“Jika pasien dengan HIV dengan sukarela mengakui statusnya, maka akan sangat dihargai. Namun apabila tidak, saya rasa harus tetap dilayani sesuai haknya,” ujar Ina kepada BBC News Indonesia.
“Tenaga kesehatan wajib menerapkan kewaspadaan standar terlepas apakah pasien memberikan info status HIV-nya atau tidak.”

Sumber gambar, Dok. Ina Agustina Isturini
Menanggapi temuan Jaringan Indonesia Positif dan masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV—terutama dari kalangan tenaga kesehatan—Ina mengatakan pihaknya akan melakukan “pemberian edukasi yang terus menerus dan penerapan universal precaution”.
“Stigma memang masih menjadi masalah di Indonesia. Pemahaman masyarakat terkait HIV masih kurang menyebabkan sering terjadi kekhawatiran yang tidak tepat,” ujar Ina.
Ina menyebut para tenaga kesehatan sudah memiliki standar untuk keamanan dan keselamatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
“Seharusnya kalau ini sudah diterapkan, risikonya bisa seminimal mungkin,” tuturnya.
“Kalaupun ada kecelakaan kerja yang menyebabkan ia berisiko terkena HIV, solusinya adalah PEP [post-exposure prophylaxis],” ujar Ina.
Apa itu PEP?
PEP alias Profilaksis Pasca Pajanan adalah pemberian obat antiretroviral (ARV) dalam waktu singkat setelah terpapar virus HIV.
Dalam konteks tenaga kesehatan, itu termasuk tidak sengaja tertusuk jarum suntik saat menangani pasien dengan HIV.
Tujuan PEP adalah mencegah virus HIV berkembang biak dan menginfeksi tubuh. Menurut WHO, pemberian PEP mengurangi risiko tertular sampai 86%
“Obat PEP harus diberikan sesegera mungkin, idealnya dalam waktu 4 jam setelah terjadi paparan, dan paling lambat 72 jam,” ujar Ina.
"Nakes yang terpapar virus HIV akibat pekerjaannya, misalnya karena tertusuk jarum suntik, akan diberikan obat PEP selama 28-30 hari," lanjutnya.
Di Indonesia, program PEP ini merupakan langkah penting dalam melindungi tenaga kesehatan dari risiko infeksi HIV, terutama setelah mengalami paparan seperti tertusuk jarum suntik yang terkontaminasi.
"Obat-obatan untuk program PEP tersedia di layanan pengobatan HIV (PDP) termasuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas," ujar Ina.
"Obat-obatan yang digunakan berasal dari program dan ketersediaannya mencukupi."
Meskipun begitu, program PEP yang di Indonesia dikhususkan untuk tenaga kesehatan pun masih menyisakan cela.
“Berapa banyak sih, distribusinya? Apa setiap puskesmas ada? Jangan jauh-jauh, ke rumah sakit kabupaten. Coba tanya-tanya? Enggak ada,” ujar dokter Boyke.
Meski mengakui PEP ini dapat membantu tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya, Boyke mempertanyakan pemerataaan distribusinya di daerah-daerah.

Sumber gambar, Getty Images
Lagi-lagi, Boyke menyoroti “ketidakmerataan, ketidaktahuan, ketidakinformasian” di seluruh Indonesia mengenai edukasi HIV.
Menurut data Kementerian Kesehatan, obat ARV (termasuk PEP) tersedia di 5.739 balai Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV yang tersebar di 4.206 Puskesmas, 1.449 RS, dan 84 klinik dan balai di 38 provinsi dan hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Kembali ke Denpasar, Winda menyayangkan masih ada tenaga kesehatan yang menurutnya masih belum teredukasi tentang HIV.
“Bagaimana mau edukasi ke masyarakat, kalau dari pihak tenaga kesehatannya tidak teredukasi? Termasuk soal PEP” ujarnya.
Winda pun berharap pemerintah—termasuk dinas kesehatan setempat—bisa memperhatikan hal ini. Sebab, menurutnya, cerita seperti ini bisa menyebar dari satu ODHIV ke ODHIV lainnya yang membuat mereka bisa-bisa menjadi putus obat.
“Untung aku yang diperlakukan seperti ini, coba orang lain?” ujarnya.